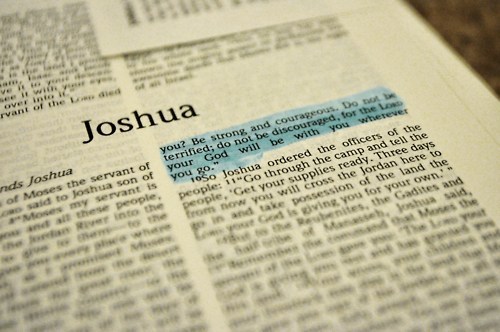|
| picturetakenfrom:weheartit.com |
Aku menoleh pada pintu kamar yang terbuka sedikit. Waktu
sudah menunjukkan pukul setengah sebelas malam, namun aku sama sekali belum
mengantuk.
“Hai,” sapanya ceria seperti biasa, ia masuk dengan setelan
jas putih miliknya.
“Selamat malam, Dokter Muda,” aku sengaja menekankan dua
kata terakhir, ia tertawa saat mendengarnya.
“Apa kabar?” Ia duduk di sisi tempat tidurku. Aku
memperhatikan kantong matanya yang menghitam, jaga malam pasti melelahkan
sekali ya? Tapi ia tetap tidak kehilangan senyumnya.
“Bisa sebaik apa sih kabar lo kalau lo mengidap leukemia?”
Lagi-lagi tawanya berderai saat mendegar pertanyaan
sarkastikku,”Jangan ngambek gitu dong. Udah bagus gue tengokin”.
“Ya, ya, ya,” aku memutar bola mata,”Makasih ya. Jadi kita
main apa hari ini?”
“Kartu?” ia mengeluarkan satu pak kartu remi dari saku
jasnya. Ko-ass macam apa yang bawa-bawa kartu di jam praktiknya?
“Great!” aku
berseru riang. Sudah tiga malam ini kami rajin menghabiskan waktu bersama. Dia,
si mahasiswa fakultas kedokteran yang sedang kebagian jaga malam di rumah sakit
khusus kanker ini benar-benar seperti pangeran berkuda putih yang Tuhan
kirimkan padaku sebelum aku mati.
“Gimana sakitnya?” ia bertanya penuh perhatian di
tengah-tengah permainan kami, tahu bahwa aku tidak bisa tidur setiap malam
karena menahan sakit.
“Masih dalam taraf yang bisa ditolerir,” aku menjawab
enteng,”Dan elo bikin gue lupa ama rasa sakitnya sekarang. Do you know? It is the pain that makes me can’t forget about this
cancer thing”.
“Elo mau tahu kabar baiknya?” ia mengangkat kedua alisnya.
“Seberapa baik sih kabar baik yang bisa gue terima?” aku
melengos, tahu bahwa penyakitku ini sudah terminal. Harapanku untuk sembuh
sudah hilang sejak penyakit ini kambuh satu tahun lalu, and I am too drained to re-experience all of those series of pain in
the ass chemo. I can die any second now.
“Jaga malam gue ditambah dua hari lagi. Jadi, gue bisa
nemenin lo lebih lama. How’s that sound
to you?”
Aku membelalak mendengarnya. Aku pikir ini hari
terakhirnya,”Kok bisa?”
“Gue nggak hapal status pasien, jadi dokter Husni nambahin
jadwal jaga gue. Kejam abis”.
“Makanya belajar,” cibirku.
“Gue nggak belajar gara-gara siapa coba?” ia tersenyum
jenaka.
“Iya, iya. Gue yang salah”.
“Haha. Elo ngambekan banget sih?” ia mengacak-acak rambutku.
“Jujur aja, gue ngiri ngeliat lo. Kita seumuran, tapi gue
nggak bisa ngelakuin apa yang lo lakuin”.
Tatapannya melunak tatkala mendengar keluhanku. “Maksud lo,
elo mau jadi mahasiswa kedokteran juga gitu?”
Aku mengangguk.
“Pasti biar bisa ketemu gue ya?”
“Huuuu… GR!” Aku meninju lengannya pelan.
Ia tergelak. “Tuh kan, ngambek lagi”.
Tiba-tiba ponselnya berbunyi.
“Alarm patrolinya nenek sihir ya?” tanyaku, nenek sihir
adalah julukan kami untuk perawat di sini.
“Yep. Gue harus cabut nih sebelum kita ketahuan.”
Aku paling benci saat seperti ini. Saat aku harus sendirian
lagi di kamar yang bau karbol dengan hanya ditemani tetesan infus.
“Tidur ya?” ia menyelimutiku.
“Gue takut. Gimana kalau gue tidur dan nggak bisa bangun
lagi?”
“Katanya nggak takut mati?”
Sejak kenal lo, gue
jadi takut mati. Takut kita nggak bisa ketemu lagi, tapi aku urung
menyampaikannya. Jadi, aku malah bertanya, “Elo janji gue nggak bakal mati?”
Ia menatapku lekat, lalu membelai kepalaku. “No. But I promise you’ll be safe and sound”.
”Gimana kalau gue bangun karena kesakitan?”
“Another dosage of morphine
would do,” Ia tersenyum lembut,”I
will make you feel no pain, that I can promise”.
“Elo mesti istirahat,” ia mengecup dahiku singkat. “Sampai
ketemu besok”.
Aku memandang punggungnya yang semakin menjauh. Berdoa dalam
hati, supaya Tuhan bermurah hati memberiku dua hari lagi untuk dapat
melihatnya. Mendengar tawa dan suaranya. Menghabiskan waktu bersamanya.